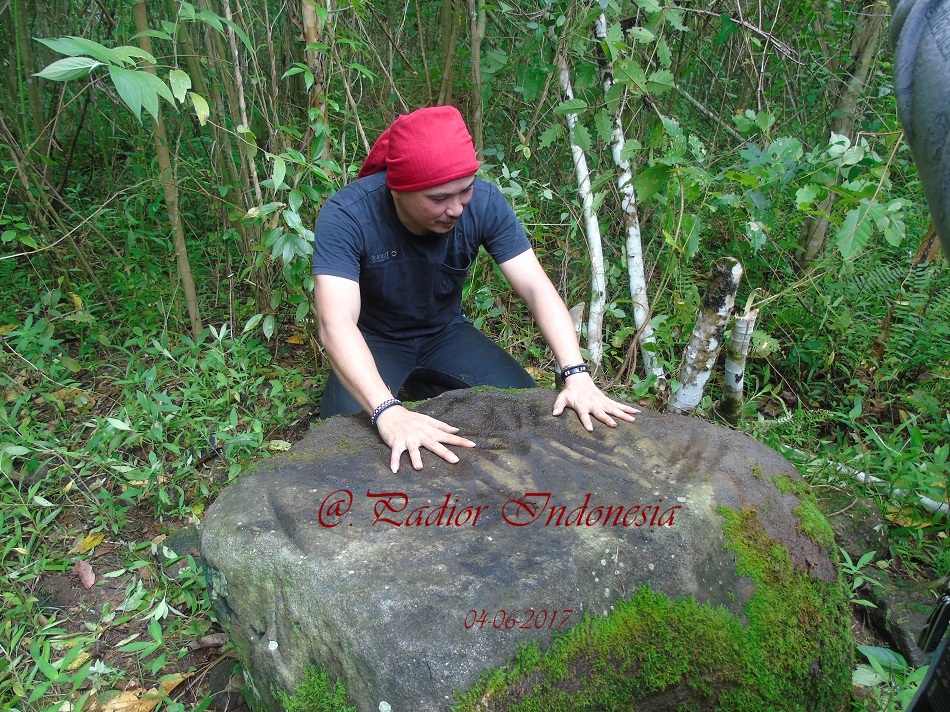Awoja sapaka se mëinang anio', ja talos lëngei nimanga- kar,
akarera in tjumangkë' e mangilëk. Ja a si makasa sera i mëinang, ja maange a se
ito' i toja'ang iitu. Ta'an mange- oka sera, iparitja-ritjakë' e ito'na.
Marengo-mange a lawiera sera i mëinang, si lawi mawuruko itu. Ja a si makasa si Toja'ang iitu makareken in tanai : „Ja
mema'pe' kua'a kolombuang aku." A si ëndokë' itu si To- ja'ang nimema' ësa
kolombuang. Tanuo i mawawa'andoo-mio' ja mangeo ita'an i Toja'ang ëng
kolombuang. Mando-mai ma-ngenao ilëkën im boondope' ën aita'ana. Itjatëka'-mange
sia,ja mio'nao iangkai-ai ja utëroka. Kuanao: „Nimindoka tu'u re'e n
aita'angku.'* Ja wulengënao-mai se pongkor isera. Mau- nëroka im bale sia. Ja
ng kuano e tow: „Ambisa sera wo, e Anak i Malënge-lëngei, nirumombito karu'
ko'?" Sowatëno i Toja'ang iitu ëng kuanao : „Ra'itja, ta'an niindo in
tjolom- buangku." Ja wueiëno i ësa tow : „Ja sapa m pangilëk(ë)mu
isera?" Kuanao: „Wene'kë' wo'on." Ja weano weta' am pa-
la'mbakangkë'.
Ta'an si Toja'ang iitu ja ra'itja nisumowat sapa-sapa. Ja
mangem tu'u si Toja'ang a si Inanga, ëng kuanao : „O Ina', waweano tu'u wene'
kanen kita." Kailëkan- ako i Toja'ang in sapaka ja roro'na kaereana
sapa-sapa, ja ng kuanao: „Mema'pe' kua'a ka'i ësa aku." Ja a si ëndokë'
iitu, ja sia nimema' ka'i ësa.
Mawawa'ando kai-mio' ruao tu'u ë mangena aitaan.
Mandoo ka'i-mai ja mangena ilëkën ën aita'ana. Pailëkënao mawuta-wuta waja e
pongkor. Wulengë- nao-mai se pongkor. Maunëroka ka'i-mange im bale si Toja'ang
iitu, ja wueiëno ka'i e tow: „Sapa n ipawe'e se pongkor(ë)mu?'' Kuano i Toja'ang
iitu: „Karaitjë' wo'o wo salanajau." Weano tu'u karai wo salana sia.
Marengo-mange a si Inanga si Toja'ang iitu ëng kuanao : „O Ina' ! wilitën-io'
ëng karaitju WO n salanaku, aiwe'e se pongkor(ë)ku niindo in tjolombuang
niema'ku." A si ëndokë' iitu, ëng kuanao ka'i: „Ja mema'pe' kua'a ka'i ësa
aku.'* Anaitu mawawa'ando-mio', tëlu tu'u ë mangena ita'an. Mandooka-mai im
boo-woondope' ja mange- nao ilëkën ën aita'ana. Pailëkënao ja mawuta-wuta waja
e pongkor se tëlu kolombuang iitu. Wulengënao-mai se pong- kor isera. Maunëroka
ka'i-mange im bale sia, ja towano ka'i e tow : „E Toja'ang i Malënge-lëngei !
sapaka ka'i n ipawe'e se pohgkor(ë)mu ?" Kuanao: „Pisow(ë)kë' wo'on."
Si Toja^ang isia ja ang karapitjë' i mainde-inde' am pa'pa'an in tow lëngei. O
weta' weano ka'i pisow sia, ta'an pisow re'e pungkut. Mande tani'tu sia rai'tja
nimera-mai. Marengo-mange a si Inanga si Toja'ang iitu, ëng kuana: „O Ina' ! wa
weano tu'u pisow kita, e Ina\ ta'am beangkupe' uting, wo sama'
itum-bal(ë)ku."
Jawo itu iema'na tumbalan. Pakaema'ana tu'u-mako itu, ja
kalingaanao se Ito'na ja mange mëlitag an talun. Ja mangem a si Ito'na sia, wo
ng kuanao : „O Ito', sa itjasale'miow, ja kumi'ite' aku." Kuano e Ito'na :
„Ma'ane' pisow ja ra'itja kaulitan, ja wo'ope' in tjumi'it; sa ko kumi'it ja
karëngan ko pongkolan in do'kos/ Ja mandepe' tina'aran in tjainde'en, ja
ra'itja tina'neina itu. Jawo si Toja'ang iitu mange a si Inanga ëng kuana: „O
Ina', sa ro'na ialer-io' walun aku, en aku ja kumi'ito' se Ito', mange mëlitag
an talun." Siituoka tu'u maja'o se Ito'na, wo sia kumi'it; susur in am
pengkoran se Ito'na, ja si Toja'ang iitu mamorak ë mawaja', oreka sia pailëkën
e Ito'na. O weta' ! itjatënaoka si lalan pareke-rekenën ësa pal am
papengkoran, ja sia ra'io nimailëk in sine'pangan e Ito'na. Ja ng kuanao : „En
aku n tinintjasangkë' e Ito'ku ja mënto'o kua'a ambia aku." Jawo si
Toja'ang iitu kumanat in a'kël, WO ng kuanao: „Tuma'taso kua'a ambia aku."
Wo sia mema'tërung pareke-rekenën tëlu ngaparas in atëp in talun. Jawo sia
mi'mbit sangapulu' ë litag, wo ilitag(ë)na, ta'an aili'tjir(ë)kë'- mio' in
tërung, Ipakalitag(ë)na-mako itu, ja sia mange an tërung. Rai'pe' nilumukut
sia, ja palinganao marëngkeko.
Ja mangena paten si wio'o. A si tëlu ngando ja puteoka i
matatar se wio'o sia, akar in aiema'oka solimai pinakom- bo'an in sera'. Ang
kaëpatan ngando ja ng kuanao: „Ma- ngerepe '-mange se Ito'ku aku."
Maja'o si Toja'ang iitu, wo sumpakëna-mange se Ito'na, Ja
ësao wangkër ë niindo, ta'am borung. Kuano e Ito'na: „O ko topukën !
nimakaerekë' tu'u-mai si Toja'ang anio'." Sowatën 1 Toja*ang iitu, ëng
kuanao: „Mëkisëra'pe' a se Ito'/ Ja wangkilano-mange koling sia, ra'itja aiwe'e
ang karapi in upus, WO ririor ka'i-mange litu, ja sia aisalo-salowo i Ito'na.
Kuano i Toja'ang itu : „O Ito' ! sa kamu masale', ja mangeo rumakut in sera'
niindoku." Kuano e Ito'na: „Awo koi! ra'itja tu'u re'e nganga' sia?
pe'tare kami m bona' lima ng^apulu' ën aita'an ja wajape' in ësa ë niindo, ja
wo'ope' iitjo!" Kuano i Toja'ang: »Ulit e Ito'/ Kuano e Ito'na: ^Sa
ka'itje' ra'itja, ja karëngan ko em pongkolanami !'* Ja maja'o tu'u sera,
ipakata'anerakë' ang kanat i oja'ang iitu m pisow. Ja itjatëka' tu'u-mange se
Ito'na, ja uli-ulit. Kuano I Toja'ang: „Sangarakut(ë)kë' ën indongku, akar iitu
ja itjamuoka." Kuanoe Ito'na: „Ja ita'tak-ai lulun kita/ Ja maja'o si
Toja'ang iitu tuma'tak lulun. Pëta'takënao si sumpakëna-mange ja ninumuwu'kë'
in tana'i : „Ja itjaupus-ai aku, tio'o ta'ta-ta'takën aku." Janta'an
iwareng(ë)naoka-mai i numuwu' : „Ta'an mande kua'a aku ta'takënu, ta'an tio'o
paina-ina'an, mande piso'nakë' ësa, ja tio'o paina-ina'an. Ta'an sa ko mange
rumakut im paalinu, ja itampengkë'-mange an somoi aku. Jawo sako nimangem am
bale, ja iwangengkë'- mange an du'u aku." Ja mangeoka a se Ito'na sia, ja
pëin- dongkë' wo'o e Ito'na.
Kuanao: „Itjaupus-ai, tio'o indo-indon ën iana, wo
kamu mangekuoka ita'tak-ai." Mangenao tu'u ita'tak-ai se Ito'na, aisawël a
si niangena-mai ririor. Jawo tu'u sia mangem am bale, ja si wisa n aitjua i
Lulun, ja ki- ni'itana, in iwëkar an du'u. Mandooka-mai im boo-woondope',ja si
Toja'ang iitu lumaes-ako wo marengoka-mange en oraso in tjuman. Ja mangem tu'u
sia a lawina, mangena pailëkën, ja alero ng kakanën am bawo i meja. Jawo sia
mangaja'ka' ëng kuana: „O inde'! si sei kua'a re'e ë nimaali-mai in anio'
?" Ja paënto-ënto'ona, jo ra'itja wana ng kumësot-ai. Kuanao : „Kumano
kua'a aku." Makakan-ako sia, ja ra'itja nimëlur in tjinanana, wo ka'i sia
lumaes. Marengoka ka'i-mange sia e mawëngio, mange tu'u sia wo pailëkënao ja niengketano n sosoloan, ja alëro ka'i ng
kakanën an dangka' i meja, Jawo sia mangaja'ka' ëng kuanao ka'i : ^Si sei kua'a
ë mauwit-ai im pakanëngku ?" Jawo ënto'ona ka'i tojo'. Paënto-ënto'ona
ka'i ja ra'itja wana ng kumësot-ai, ja kumano ka'i sia. A si tëlu ngando
mëngulu-ngulur tanu si tjatare. Kaëpatan ngando ja si Lulun numuwu' ka'i ëng
kuana : „Sapaka ko ja mange mamuei im bale i Tjolano/ Ja ng kuano i Toja'ang iitu: „O ndo'on! sapao ndo'on ën
iwe'eku iitu, ma'ane' tare karaiën-itjo aku ja ra'itja kaulitan, ja wo'ope' i
muei im bale i Tjolano?" Kuano i Lulun: ,0 mangem beta'-wo!" Ja
mangen tu'u si Toja'ang, mange a si Tjolano, wc sia muei a si Tjolano: ^Ra'itja
pawu'unën ëm bale i Tjolano?'* Kuano i Tjolano: „Pawu'unën, ta'an sa n iasa
tëlësanuka, ja irojor(ë)kukë' ëm baja-waja in an sangkum im bale." Kuano i
Toja'ang: „Mandepe' ja.'
Kuano i Tjolano: „Ja mai ambia'i-wo e!" Maio
tu'u si Toja'ang ëng kuano i Tjolano : „Ja sumereo-mio' im pariri, se ruakë'
ka'itje' anio' ëm buta-wutan im pera. Sa ka'itje' ra'itja indonu, ja karë- ngan
ko em pongkolan." Ja marengo-mange si Toja'ang ëng kuanao a si Lulun : „Ja
aipapalawi-lawi'muo aku, en aku ja tina'aran i Tjolano in sa ra'itja kapopoan,
ja karëngan aku en dantongënoka. Mëwëra-wëra'kë' tu'u! rua m pariri, paka-
wuta-wutan im pera." Kuano i Lulun : „Tio'o ko mainde-inde'a siitu,
janta'an sapaka ko ja mindo-mai rua piso'na an iaku, tio'o ipapai-pailëk, oreka
wana mailëk. Ja itjatëka'-mange ko, ja ilëpok-ange a se pariri rua n iitu,
mëkele ësa a si ësa wo si ësa."
Itjatëka' tu'u-mange sia, ja kini'itana. Ira'mbas tu'u-mio'
itu ja pailëkënao m pariri ja kinuwuano im pera. Ja ng kuano tu'u i Tjolano :
„Ja rumojoro tu'u kami." Ipakarojor(ë)na-mako m baja se ambitu, ja
pailëkëno i Toja'ang in sapaka si wale itu ja talos wangkër. Kuano i Toja'ang:
„Ja sapa tu'u ën itiruw(ë)ku si wale anio'? Mëna'-mio' a si ru'una anio' aku,ja
si seipe' ka'i ë mëngëna-ngëna' a se ru'una walina?" Ja marengo-mange sia
, ëng kuanao : „Ja aipapalawi-lawi'muo aku, mëwëra-wëra'kë' tu'u re'e, ën
itiruw si wale iitu!" Kuano i Lülun : „Mëné-pënës eta'-wo.
Apaka aku ja
paalintjë'-mange im bëngi, tio'o ipapai-pailëk, mangekë' iwëta'-mio' a si wuni
an unër, wo kusi'angkë'-mange, tio'o pauntë-untëpën ën iitu. litjo ja
mëna'kë'-mange a si ru'una an sangawiwi." Ja kini'itan tu'u i Toja'ang.
Mandooka-mai ja sia ka'i lu- maeso; ja marengoka-mange sia, ja pailëkënao ja
nimatiruwo in doko' si wale iitu nitjumëli-mai an doko' i Tjolano. Pailë- këna
ka'i ja niompërano in tjanën. Kuanao ka'i : „Si sei kua'a tu'u re'e ë mauwit-ai
im pakanëngku ?" Paënto-ënto*ona- mai, ja ra'itja wana ng kumësot-ai ; ja
ng kuanao : „Ja ku- mano kua'a tare aku." Makakan-ako sia, ja ra'itja
nimëlur in tjinanan, wo tumintjas ka'i. Mareng ka'i-mange sia, tani'tukë' ka'i.
Ja a si tëlu ngando ja nimëngulu-ngulur tani'tu. Ja ang kaëpatan ngando, ja ng
kuano i Toja'ang iitu: „Ja ilukut(ë)- kupe'." A si ëndooka tu'u itu
ilukut(ë)nao. Pareke-rekenëno tu'u i Lulun, ja nilumaeso ka'i si Toja'ang,
ra'itja, e nilumu- kut si mawe'e im pakanëna, ja ra'ipe' tu'u ure sia ë nilumu-
kut-io\ ja kumësoto-mai si Lulun.
Pailëkëno i Toja'ang ja ësa wewene lo'or, ja
m bërëna tanu ng kasëndot i ëndo, ën su- luna ja paser(ë)kë' wo m ba'ang ja
paser(ë)kë* ka'i. Ja tim- boianao-mange sia wo ng kuano i Toja'ang: „litjoo
tu'u re'en ë mawe'e im pakanëngku." Ja sowatëno i Wewene: „laku, ta'an apa
ko ja muntëp-ai a si wuni anio' wo ko sawëlangku karai." Ja muntëpo
tu'u-mange sera, ja pailë-ilëkën i Tojaang ë Lulun ra'io wia. Ja sumondolo tu'u
in tjarai e Walanda si Toja'ang, wo sera lumaes mëwali-wali. Wo sera pailëkën i
ësa tow, WO mangena iowër a si Tjolano ëng kuana: „O Kolano, wona' ësa kolano
si mëngëna-ngëna' am bale i Tjo- lano-wo;" jawo sia mangaja'ka' wo mainde'
am pa'pa'an oreka ipëset(ë)na ng kakolanoana. Anaitu wo sia rumu'ndu' se su-rarona
pitu ngapulu' mange wo'o mindo se ambalesa. Ma- ngeoka sera, ja an tëmbërane'
sera, ja mëlutawo wo'o se suraro, wo iangkaiera-mai n sinapang, ja makauluroka
tani'tu, ra'io toro itjapëku'. Ja kalingaano i Tjolano, ja i nimaka- ilangkë'
se surarona, ja sia rumu'ndu'pe' ka'i-mange suraro pareke-rekenën maatus. Ja
mangeoka sera, ja an tëmbërane' sera, ja iangkaierao-tnai n sinapang.
Itjaiangkaiera in sinapang, « ja sera makauluroka ka'i tani'tu.
Ja kalingaan ka'i-niako i Tjolano in tani'tukë' ka'i se sii-
rarona, ja ng kuanao: ,,Ja iaku kua'a ë mëtët-ange." Ja min- doo-mai in
sa'mbël sia, wo sia mange. Itjatëka'-mange sia, ja pailëkënao tu'u, ja uli-ulit
si tuama ja Walanda talos lo'or, tani'tuka ka'i si wewene talos lo'or
nimangakar. Ja makaso- sor-ange sia, ja weso'onao-mai n sa*mbël wo
ipëparak(ë)na isera in ambalesa; itjaiangkai-ai in sa*mbël, ja makauluroka
tani'tu. Ja ng kuanerao in ambalesa : „Ja iwajape'-mio' sia- wo, akar in
sangaoras sia ra'io itjapëku'." laka-akar tu*u si Tjo- lano i mëkiampung,
ëng kuana : „Sa ro'na ja sama'ano-mai aku WO iitjooka ka'itje' ng kolano, ta'an
iaku ng kumarua iitjo." Jawo mapo'o-po'ow-io' a si ëndo iitu n isiaoka ng
ko- lano. Ja ng kuanao : „Ja mema'pe' kua*a kasale-sale'an kita, en aku ja
mëkitowape' se mapërenta am bawa'ku-mio', wo se po'o-po'ow."
Ja ipëkiangenao-mai se Ito'na. Mangeoka se airu'ndu'-ma- nge
ja sera mangaja'ka' ëng kuanerao: „Itjatambisa itu wo tani'tu, WO kami ënotën
ang kasale-sale'an i Tjolano?" Ja kuano e airu'n-du'-mange : „Aita'ar-ai
an itjami, ja karëngan kine kamu e mange." Jawo tu'u sera mange, ja
itjatëka' tu'u- mange sera, ja alero m baja kakanën, wo se aka im banua tuama
ja ambituo waja. Am pa'pa'an in ambituo waja, ja kuano i Tjolano : „Ja en alero
waja, ja lumukuto kita." Wo sera kuman. Tawio makakan ja kuano i Tjolano
in tjumua a se mateir ang kakanën : „Ja e makakano-sa, ja iwaja'o-mai si
paëlëpën iana." Iwaja'erao tu*u, aito'tol a si Tjolano wo mange a se
mapërenta am bawa'na-mio' wo mange a se Ito' i Tjolano, ja itjaitu'tukera-mio'
am paëlëpan, ja itjalengket(ë)- kë'-mange am biwi m paëlëpan, wo nilumengket
ka'i-mio' am palukutan m pë'narera, iaka-akarera i mëkia-kiampung a si makaito'
isera. Ja sowatëno i Tjolano itu ëng kuatiao : „Jawo mamëndamo-mange kamu, an
tutuw(ë)ku in toja'ange'-wo, pi- iialënge-Iëngeimiow(ë)kë*-mio'-wo, janta'an
pëndamëniow-mange m bawaer(ë)ku an itjamu. Anae kamu ja sangasërap ën am- bana.
Jawo sa kamu ra'io n a si ukuman iana, ja kamu in Ito'ku WO se toja'angiow ja maindooka ataku waja."
Tani'tu sera nimaindooka ata i makaito' isera, sera in ambalesa wo se toja'ang.
Siitukë'.