Mawale merupakan lokasi pemukiman tertua suku Minahasa purba
dan diketahui memiliki sejarah panjang pemukiman awal sampai tersebarnya
sub-etnis Minahasa di jasirah Minahasa. Mawale yang berarti mendirikan
pemukiman merupakan bahasa tontemboan yang merupakan bahasa pengantar suku
minahasa sub etnis tontemboan yang didalamnya masyarakat Tumompaso. Namun
pengertian mawale sendiri berasal dari kata wale yang berasal dari istilah
Austronesia: bale yang berarti ‘gedung umum’. Wale dalam bahasa-bahasa
minahasa bisa juga berarti rumah, desa,
kandang, juga rahim. Mawale juga berarti hidup bersama dalam rumah yang sama,
sementara ‘rumah’ umumnya digunakan juga untuk melukiskan keturunan yang sama
dikawasan melayu dan Austronesia. Rumah yang berfungsi sebagai alat pertahanan
dari gangguan cuaca dan binatang buas dihutan, untuk pertama kalinya didirikan
disini.
Sehingga waleure (rumah tua) juga identik dikaitkan dengan perkampungan
ini. Lokasi wilayah perkampungan mawale ini diperkirakan sebesar kurang lebih
lima belas hektar terdapat dikepolisian desa talikuran di sebelah utara desa
pinabetengan dan di bagian timur desa kanonang yang hingga saat inipun masih
dinamakan demikian. Sebagai satu tanda pembuktian sejarah masih adanya terdapat
kuburan batu bernama waruga disitu. Waruga ini menurut penelitian, yang paling
tua berasal pada abad kedua sebelum masehi. Hal inipun menjadi lebih menarik
dimana mitos-mitos yang ada hingga saat ini, maupun para pakar sejarah dan
kebudayaan belum dapat mengungkap arti kata, proses pembuatan dan pengerjaan
serta upacara-upacara dibaliknya namun sangat disesalkan sudah banyaknya waruga
di tempat ini yang dibawah keluar oleh pemerintah sulut dimasa pemerintahan
Gubernur H.V. Worang, dan banyaknya perusakan dari tangan tangan tidak
bertanggung jawab.
Manalun
atau pergi kehutan untuk berburu adalah pekerjaan utama disamping bercocok
tanam atau bertani dalam bahasa Tumompaso adalah mangu’ma merupakan mata
pencaharian orang mawale dahulu dengan budaya gotong royong ma’ando (bekerja
seharian) yang kemudian berkembang menjadi mapalus: (ma’pa) dan (elusan) yaitu
kebiasaan orang saat ma’ando membawa bekal dengan nasi yang dibungkus daun
elusan. Dengan petuah leluhur yang terpelihara sampai sekarang yaitu: sa ko
kumesot tumawoy pe mondol nendo, sa ko
mareng makapum wo e nendo artinya jika kau pergi bekerja sebelum matahari
keluar, demikianpun jika kamu pulang setelah matahari terbenam. Demikianpun
filosofi sitou timou tumou tou yang dipopulerkan oleh Sam Ratulangi merupakan
akar budaya yang hidup berkembang dari negeri ini yaitu : sako matou, touen si
tou walina (jika kamu menjadi manusia, manusiakanlah orang lain) dan kemudian
berkembang menjadi Amanat Sang Pemimpin (Nuwu I Tua) (Akad Se Tu’us Tumow Wo Temow Tou) diambil
dan dijadikan semboyan/ pandangan hidup masyarakat sulawesi utara, indonesia bahkan
dunia hingga saat ini.
Bahwa jauh
sebelum pekuburan waruga menjadi tempat pekuburan orang mawale yang
dimasukan kedalam batu dan ditutup
rapat, masyarakat mawale lebih mengenali cara mengubur mayat dalam peti kayu
(pinipakan) yaitu semacam kayu bulat besar yang didalam/ tengahnya dilubangi.
Seiring dengan waktu cara penguburan ini ditinggalkan dengan alasan adanya
wabah sampar dan kolera di mawale yang begitu hebat pada saat itu dan berganti
dengan cara baru yang pada akhirnya kita kenal dengan waruga. Walaupun cara
penguburan waruga sudah berkembang disaat ini akan tetapi traumatik yang besar
bagi sebagian masyarakat mawale disana masih tetap tinggi dan ditambah pula
dengan kepercayaan masih adanya roh jahat penyebab penyakit yaitu angin jahat
(reges lewo) . Dengan adanya wabah ini otomatis penduduk dimawale makin
berkurang dan sudah adanya pemikiran bagi tua-tua atau para Tonaas di mawale
mencari perkampungan baru.
Dengan semakin padatnya pemukiman awal ini, suku Minahasa awal yang tersisa saat musyawarah pertama dan kedua di watu Pinawetengan untuk penyebaran dan pembagian wilayah pemukiman di Tanah Minahasa memaksa penduduk Mawale bergeser lebih kearah timur mendirikan pemukiman baru di lokasi Timbukar Kamanga. Timbukar kamanga ini menjadi pemukiman kedua yang tersisa saat sub-etnis Minahasa dibagi.










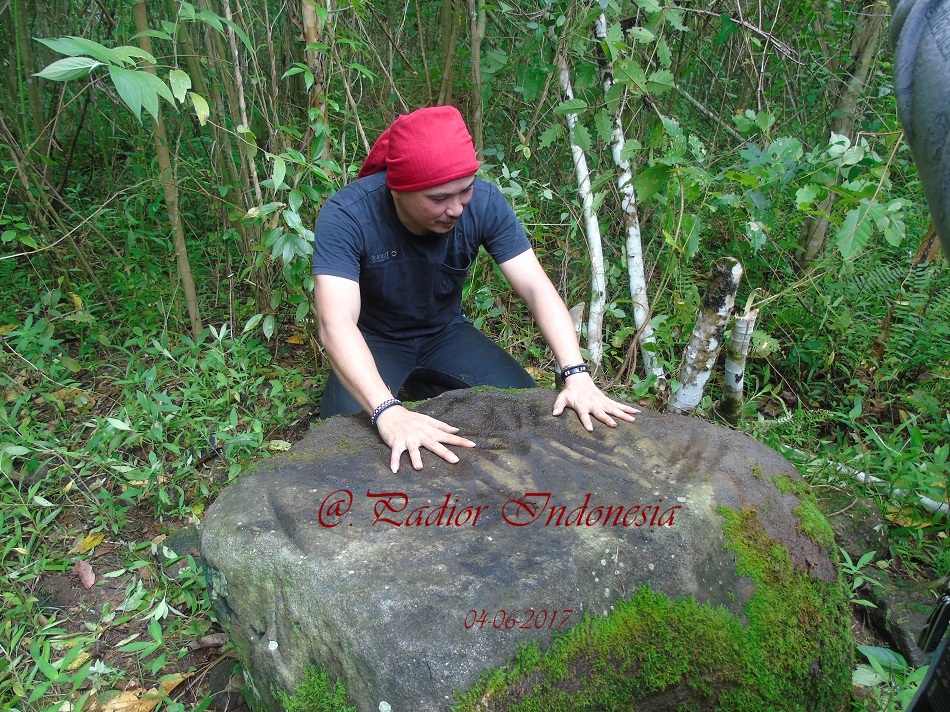










0 komentar:
Posting Komentar